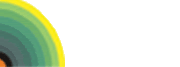Di tengah keheningan malam Madinah, sang pemimpin umat Umar bin Khattab berjalan menyusuri lorong-lorong kota. Kegiatan ini adalah sebuah kebiasaan bagi beliau, dengan tujuan agar lebih dekat dengan kaum muslimin. Saat itu, hampir menjelang dini hari, tiba-tiba saja beliau mendengar dari bilik rumah seseorang, sebuah percakapan antara Ibu dan anak.
“Nak, campurkanlah susu yang engkau perah tadi dengan air,” kata sang ibu.
“Jangan ibu. Amirul mukminin sudah membuat peraturan untuk tidak menjual susu yang dicampur air,” jawab sang anak.
“Tapi banyak orang melakukannya Nak, campurlah sedikit saja. Lagipula insyaallah Amirul Mukminin tidak mengetahuinya,” kata sang ibu mencoba meyakinkan anaknya. “Ibu, Amirul Mukminin mungkin tidak mengetahuinya. Tapi, Rab dari Amirul Mukminin pasti melihatnya,” tegas si anak menolak.
Mendengar percakapan ini, berurailah air mata Umar bin Khattab. Karena subuh menjelang, bersegeralah beliau ke masjid untuk memimpin shalat Subuh. Sesampai di rumah, dipanggilah anaknya untuk menghadap dan berkata, “Wahai Ashim putra Umar bin Khattab. Sesungguhnya tadi malam saya mendengar percakapan istimewa. Pergilah kamu ke rumah si anu dan selidikilah keluarganya.”
Ashim bin Umar bin Khattab melaksanakan perintah ayahnya ini Sekembalinya dari penyelidikan, dia menghadap ayahnya dan mendengar ayahnya berkata, “Pergi dan temuilah mereka. Lamarlah anak gadisnya itu untuk menjadi isterimu. Aku lihat ia akan memberi berkah kepadamu dan anak keturunanmu, insya Allah. Mudah-mudahan pula ia dapat memberi keturunan yang akan menjadi pemimpin bangsa.”
Begitulah. Ashim bin Umar pun tidak banyak komentar mengenai permintaan ayahnya ini. Tak lama, menikahlah Ashim dengan anak gadis tersebut. Dari pernikahan ini, Umar bin Khattab dikaruniai cucu perempuan bernama Laila, yang dikemudian hari dikenal dengan nama Ummi Ashim.
Suatu malam setelah itu, Umar bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat seorang pemuda dari keturunannya, dengan kening yang cacat karena luka. Pemuda ini memimpin umat Islam. Mimpi ini diceritakan hanya kepada keluarganya saja. Saat Umar meninggal, cerita ini tetap terpendam di antara keluarganya.
Pada saat kakeknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab terbunuh pada tahun 644 Masehi, Ummi Ashim turut menghadiri pemakamannya. Kemudian Ummi Ashim menjalani 12 tahun kekhalifahan Ustman bin Affan sampai terbunuh pada tahun 656 Maserhi. Setelah itu, Ummi Ashim juga ikut menyaksikan 5 tahun kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a. Hingga akhirnya Muawiyah berkuasa dan mendirikan Dinasti Umayyah.
Pergantian kekuasaan dari Sahabat Ali kepada Sahabat Muawiyah, ternyata membawa perubahan juga dalam tubuh kaum muslimin. Penguasa mulai memerintah dalam kemewahan. Setelah penguasa yang mewah, penyakit-penyakit yang lain mulai tumbuh dan bersemi. Ambisi kekuasaan dan kekuatan, penumpukan kekayaan, dan korupsi mewarnai sejarah Islam dalam Dinasti Umayyah. Meski negara bertambah luas, penduduk bertambah banyak, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, tapi orang-orang semakin hampa dari ukhuwah persaudaraan, keadilan dan kesahajaan Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.
Status kaya-miskin mulai terlihat jelas, posisi pejabat-rakyat mulai terasa. Kafir dhimni pun mengeluhkan resahnya, “Sesungguhnya kami merindukan Umar, dia datang ke sini menanyakan kabar dan bisnis kami. Dia tanyakan juga apakah ada hukum-hukumnya yang merugikan kami. Kami ikhlas membayar pajak berapapun yang dia minta. Sekarang, kami membayar pajak karena takut.”
Kemudian Muawiyah membaiat anaknya Yazid bin Muawiyah menjadi penggantinya. Akan tetapi, putra Yazid, Muawiyah bin Yazid, tidak seperti ayahnya. Dia memilih pergi sehingga singgasana dinasti Umayah kosong. Terjadilah rebutan kekuasaan dikalangan bani Umayah. Abdullah bin Zubeir, seorang sahabat utama Rasulullah dicalonkan untuk menjadi amirul mukminin. Namun karena ada konspirasi, maka Marwan bin Hakam yang berasal dari bani Umayah dari keluarga Hakam, mengisi posisi kosong itu dan meneruskan sistem dinasti. Marwan bin Hakam memimpin selama sepuluh tahun lebih.
Saat itu, Ummi Ashim menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan sendiri adalah Gubernur Mesir di era khalifah Abdul Malik bin Marwan (685 – 705 M) yang merupakan kakaknya. Abdul Malik bin Marwan adalah seorang shaleh, ahli fiqh dan tafsir, serta raja yang baik, dan terlepas dari permasalahan ummat yang diwarisi oleh ayahnya (Marwan bin Hakam) saat itu.
Dari perkawinan itu, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dilahirkan di Halawan, kampung yang terletak di Mesir, pada tahun 61 Hijrah. Umar kecil hidup dalam lingkungan istana dan mewah. Saat masih kecil Umar mendapat kecelakaan. Tanpa sengaja seekor kuda jantan menendangnya sehingga keningnya robek hingga tulang keningnya terlihat. Semua orang panik dan menangis, kecuali Abdul Aziz seketika tersentak dan tersenyum. Seraya mengobati luka Umar kecil, dia berujar, “Bergembiralah engkau wahai Ummi Ashim. Mimpi Umar bin Khattab insyaallah terwujud, dialah anak dari keturunan Umayyah yang akan memperbaiki bangsa ini.“
Saudaraku, semua ini merupakan pelajaran berharga bahwa sebuah keimanan yang ikhlas kepada Allah, akan mengantarkan pada kebahagian yang sejati. Lihatlah, kepercayaan Umar bin Khattab untuk menikahkan anaknya pada seorang gadis yang berkata, “Tapi, Rab dari Amirul Mukminin pasti melihatnya,”telah menghadiahkan dirinya seseorang dari keturunannya sendiri yang shalih dan menjadi pemimpin umat, dialah Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah…
Berawal dari Sebuah Keimanan
Label: akhlak, Ibroh, Nikah | author: Tim Embun TarbiyahPernyataan Empat Imam tentang madzhab dan kewajiban mengikuti As-sunnah
Label: Aqidah, Syariat | author: Tim Embun TarbiyahMasih seringkali ada orang yang rela mati demi sesorang atau golongannya, meskipun orang yang dianggap paling istimewa atau golongan itu sudah jelas kesalahannya. Atau juga sering dikatakan sebagai taqlid buta (Tidak ada yang berbuat taqlid melainkan seorang yang fanatik atau dungu), sikap yang terlalu berlebih-lebihan terhadap golongannya tanpa di dasari dengan ilmu. Lepas dari itu semua mari kita renungkan pendapat imam 4 seperti Al-Imam Ahmad, Al-Imam Asy-Syafi’i, Al-Imam Abu Hanifah, dan Al-Imam Malik berikut.
Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah
Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah ulama yang paling banyak mengumpulkan hadits dan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Sampai-sampai beliau tidak suka dengan kitab-kitab yang memuat permasalahan tafri’ (membagi-bagi agama menjadi ushul [pokok] dan furu’ [cabang] dan ra’yu [rasio]).
1. “Janganlah engkau taqlid kepadaku, jangan pula kepada Malik, Syafi’i, Al-Auza’i, atau Ats-Tsauri. Akan tetapi ambilah (agama itu) dari sumber dimana mereka mengambil.”
2. “Pendapat AL-’Auza’i, begitu pula Malik, dan Abu Hanifah seluruhnya hanya pendapat dan sama nilainya di sisiku. Sedangkan hujjah itu terdapat pada atsar.”
3. “Barangsiapa menolak hadits rasulullah shalallahi ‘alaihi wasalam maka dia berada ditepi jurang kehancuran.”
Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullah
1. “Tidak ada seorang pun melainkan pasti luput darinya satu sunnah rasulullah shalallah ‘alaihi wasalam. Maka seringkali saya katakan, suatu ucapan atau merumuskan suatu kaidah tetapi hal itu bertentangan dengan sunah rasulullah shalallahi ‘alaihi wasalam, maka ucapan yang disabdakan rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalam adalah pendapatku.”
2. “Kaum muslimin bersepakat bahwa siapa saja yang jelas baginya sunah rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalam maka tidak halal meninggalkannya hanya karena ucapan seseorang.”
3. “Bila kalian mendapati dalam kitabku suatu hal yang menyelisihi sunnah rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalam, maka berkatalah dengan sunnah rasulullah dan tinggalkanlah ucapanku!”
4. “Bila telah shahih suatu hadits maka itulah madzhabku”
5. “Engkau lebih mengetahui hadits dan rawi-rawinya dibanding aku, maka bila ada hadits yang shahih beritahulah aku tentang keberadaannya, di Kufah atau Bashrah atau syam hingga aku berpendapat dengan hadits itu bilamana hadits tersebut shahih.”
6. “Setiap permasalahan dimana telah shahih padanya hadits dari rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalam menurut ulama pakar hdits namun bertentangan dengan ucapanku, maka aku rujuk darinya dimasa hidupku atau sepeninggalku nanti.”
7. “Jikalau kalian melihatku mengungkapkan suatu pendapat sementara telah shahih hadits dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasalam yang bertentangan dengannya maka ketahuilah bahwa pendapatku tidak berguna.”
8. “Setiap apa yang aku ucapkan sementara ada hadits shahih dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasalam bertentangan dengan ucapanku maka hadits tersebut lebih layak diikuti dan janganlah kalian taqlid kepadaku.”
9. “Setiap hadits yang shahih dari Nabi shallahu ‘alaihi wasalam maka hal itu adalah pendapatku walaupun kalian belum mendengar darinya.
Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah
1. “Bila telah shahih suatu hadits maka itulah pendapatku”
2. “Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapan kami selama dia belum mengetahui darimana kami mengambil ucapan tersebut.” Dalam riwayat lain: “Haram bagi siapa saja yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa menggunakan ucapanku.” Ditambahkan dalam riwayat lain: “Karena kami adalah manusia biasa, bisa jadi kami mengatakan demikian di hari ini kemudian kami rujuk darinya di keesokan harinya.”
3. “Jika aku mengatakan suatu ucapan yang bertentangan dengan Kitabullah Ta’ala dan kabar dari Ar-Rasul Shalallahu ‘alaihi wasalam maka tinggalkan ucapanku tersebut.”
AL-Imam Malik bin Anas rahimahullah
1. “Aku hanyalah seorang manusia biasa, terkadang salah dan terkadang benar, maka perhatikanlah pendaptku. Setiap yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka ambilah dan setiap yang tidak sesuai dengan keduanya maka tinggalkanlah!”
2. “Tidak ada seorang pun setelah Nabi shalallahu ‘alaihi wasalam yang bisa diambil atau ditinggalkan ucapannya kecuali hanya Nabi Shalallahu ‘alaihi wasalam.”
3. Berkata Ibnu Wahb: “Aku mendengar Imam Malik ditanya tentang hukum menyela-nyela jari kaki ketika wudhu, beliau menjawab, “Hal itu tidak wajib bagi manusia.” Ibnu Wahb melanjutkan ucapannya, “Maka akupun membiarkan beliau hingga manusia di sekeliling beliau mulai berkurang, kemudian aku berkata, “Kami memiliki hadits tentang hal itu.” Imam Malik bertanya, “Apa itu?” Aku pun menjawab, “Telah menceritakan kepada kami Al-Laits bin Sa’ad, Ibnu Lahi’ah, dan Amr bin Al-Harits dari Yazid bin Amr Al-Mu’afiri dari Abu Abdurrahman Al-Hubully dari AL-Mustaurid bin Syadad Al-Qurasy, bahwa ia berkata. “Aku pernah melihat Rasulullah shalallhu ‘alaihi wasalam menggosok antara jari jemari kakinya dengan kelingking beliau.” lalu beliau (Imam Malik) berkata, “Hadits semacam ini berderajat hasan dan aku belum pernah mendengarnya sama sekali selain saat ini.” Kemudian aku mendengar beliau setelah itu ditanya tentang hal itu, maka beliapun memerintahkan untuk menyela-nyela jari jemari tersebut.”
Demikianlah ucapan-ucapan para imam, semoga Allah subhana wata’ala meridhai mereka. Amiin
[Diambil dari Tuntunan Shalat Nabi, Karya Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Edisi bahasa indonesia terbitan Ash-Shaf Media] [Edisi asliya berjudul Shifatush Shalaati An-Nabiyi Shalallahu 'alaihi wasalam min Al-Tabkbiiri ilaa At-Tasliimi Ka-annaka Taraahaa, Terbitan Maktabah Al-Ma'aarif - Riyadh]
Keagungan Isteri Seorang Mujahid
Label: Dunia Akhwat, Ibroh, Muhasabah | author: Tim Embun TarbiyahLelaki berumur enam puluh tahun itu memasuki rumahnya di Madinah. Nyaris tak mengenali lagi rumah yang pernah ditinggalinya itu. Ia menemukan rumah itu, saat menyusuri jalan-jalan di kota Madinah, yang sudah ramai.
Rumahnya yang sangat sederhana itu, pintunya agak terbuka, dan nampak lengang. Lelaki itu meninggalkan rumahnya, tiga puluh tahun lalu, dan waktu itu isterinya masih belia, dan menjelang melahirkan anak pertamanya.
Lelaki tua itu meninggalkan Medinah pergi berjihad ke negeri yang sangat jauh. Ia berangkat bersama pasukan muslimin. Membuka Bukhara dan Samarkand, dan sekitarnya, yang terletak di Asia Tengah. Begitu jauh perjalanan jihad bersama pasukan muslimin, mengarungi samudera padang pasir, menembus perjalanan beribu-ribu mil dari kota Madinah. Sungguh sangat luar biasa para mujahidin itu. Kepergiannya dengan tekad dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla.
Menjelang Isya’ dengan kuda yang dituganginya itu, prajurit tua itu, memasuki kota Madinah, yang masih ramai, dan melihat kehidupan yang tidak berubah, sesudah ditinggalkannya selama tiga puluh tahun. Namun, ingatannya yang tajam, akhirnya lelaki tua itu, menemukan rumahnya kembali, yang masih tampak sederhana, dan didapati pintunya sedikit terbuka. Kegembiraan menggelayut, dan merasa yakin bertemu dengan kembali dengan isterinya yang lama ditinggalkan itu.
Si penghuni rumah melihat ada orang yang masuk rumahnya, maka lelaki yang ada di atas, langsung melompat, dan turun sambil membentak lelaki tua yang datang itu, “Engkau berani memasuki rumah dan menodai kehormatanku malam-malam, wahai musuh Allah?”. Si penghuni rumah mencengkeram leher lelaki tua, seraya mengatakan, “Wahai musuh Allah, demi Allah aku takkan melepaskanmu kecuali di muka hakim”, sergahnya.
Lelaki tua yang baru datang itu berkata, “Aku bukan musuh Allah dan bukan pernjahat. Ini rumah milikku, kudapati pintunya terbuka lalu aku masuk”. Lelaki tua itu melanjutkan, “Wahai saudara-saudara, dengarkanlah. Rumah ini milikku, kubeli dengan uangku. Wahai kaum, aku adalah Farrukh. Tiadakah seorang tetangga yang masih mengenali Farrukh yang tiga puluh tahun lalu pergi berjihad fi sabilillah?”
Bersamaan itu, ibu si empunya rumah yang sedang tidur itu bangun oleh keributan, lalu menengok dari jendela atas dan melihat suaminya sedang bergulat dengan darah dagingnya sendiri. Lidahnya nyaris tak berucap. Dengan nada yang kuat berseru, “Lepaskan .. lepaskan dia, Rabiah … lepaskan dia, putraku, dia adalah ayahmu .. dia ayahmu … Saudara-saudara sekalian tinggalkan mereka, semoga Allah memberkahi kalian. Tenanglah, Abu Abdirrahman, dia putramu .. dua putramu .. jantung hatimu …
Lalu, Ar-Rabi’ah mencium tangan ayahnya. Orang-orang meninggalkan keduanya. Setelah itu, isterinya Ummu Rabi’ah menyambut suaminya dan memberi salam. Ummu Rabi’ah tak mengira bahwa ia akan bertemu kembali dengan suaminya yang pergi berjihad selama tiga puluh tahun itu.
Saat-saat bahagia antara Farrukh dengan Ummu Rabi’ah, terkadang duduk berdua, sambil bercerita keduanya selama berpisah tiga puluh tahun. Mereka mendapatkan kebahagiaan kembali, keduanya dapat bertemu, meskipun sekarang suaminya telah berumur enam puluh tahun. Namun, saat itu muncul kekawatiran dari Ummu Rabi’ah tentang uang yang pernah dititipkan oleh suaminya dahulu, dan ia harus menjaganya. Karena uang yang dititipkan suaminya itu, habis untuk membiayai pedidikan putranya senilai 30.000 dinar. “Percayakah Farrukh bahwa pendidikan putranya itu menghabiskan 30.000 dinar”, gumam Ummu Rabi’ah.
Selagi pikirannya mengelayut itu, tiba-tiba Farrukh, yang duduk disampingnya itu berkata, “Aku membawa uang 4.000 dinar. Ambillah uang yang akut titipkan kepadamu dahulu. Kita kumpulkan lalu kita belikan kebun atau rumah, dan akan kita ambil sewanya”, ucap Farrukh kepada Ummu Rabi’ah.
Pembicaraan terputus saat adzan datang. Farrukh bergegas menuju masjid, seraya menanyakan, “Mana Ar-Rabi’ah?’ Isterinya menjawab, “Dia sudah lebih dahulu berangkat ke masjid. Saya kira engkau akan tertinggal shalat berjama’ah”. Dia segera shalat, dan sesudah itu pergi ke Rhaudah mutharah, berdo’a di dekat makam Rasulullah, karena betapa rindunya dia dengan Rasulullah.
Saat mau meninggalkan masjid, begitu ramai orang yang sedang mengelilingi seorang ulama, yang belum pernah melihat sebelumnya. Mereka duduk melingkari Sheik itu. Sampai tak ada tempat yang kosong untuk dapat berjalan. Farrukh mengamati, ternyata orang-orang yang hadir, ada yang sudah lanjut usia, anak-anak muda, mereka semua duduk sambil menghamparkan lututnya. Semuanya menghadapkan pandangan kepada Sheikh.
Farrukh itu berusaha melihat wajah Sheikh yang luar biasa itu, tetapi tak dapat, karena begitu banyaknya orang yang mengelilinginya. Sampai saat majelis itu usai. Orang-orang meninggalkan masjid. Kemudian di tengah-tengah suasana yang sudah mulai sepi itu Farrukh bertanya kepada salah seorang yang masih tinggal di masjid itu.
Farrukh: “Siapakah Sheikh yang baru saja berceramah itu?”
Fulan: “Apakah anda bukan penduduk Madinah?”
Farrukh: “Saya penduduk Madinah”.
Fulan: “Masih adakah di Madinah ini orang yang tak mengenal Sheikh yang memberikan ceramah itu?”
Farrukh: “Maaf, saya benar-benar tidak tahu, karena saya sudah meninggalkan kota ini sejak 30 tahun yang lalu, dan baru kemarin tiba”
Fulan: “Tidak apa. Duduklah sejenak, saya akan menjelaskannya. Sheikh yang anda dengarkan ceramahnya itu adalah seorang tokoh tabi’in. Termasuk diantara ulama yang paling terpandang, dialah ahli hadist di Madinah, fuqaha dan imam kami, meksipun masih sangat muda”. Majelisnya dihadiri oleh Malik bin Anas, Abu Hanifah, An-Nu’man, Yahya bin Sa’id Al-Anshari, Sufyan Tsauri, Abdurrahman bin Amru Al-Auza’I, Laits bin Sa’id dan lainnya”.
Farrukh: “Tetapi anda belum menyebutkan namanya?”
Fulan: “Namanya adalah Ar-Rabi’ah Ar-Ra’yi”.
Farrukh: “Namanya Ar-Rabi’ah Ar-Ra’yi?”
Fulan: “Nama aslinya Ar-Rabi’ah, tetapi para ulama dan pemuka Madinah biasa memanggilnya Ar-Rabi’ah Ar-Ra’yi. Karena setiap menjumpai kesulitan tentang nash dari Kitabullah yang tidak jelas, mereka selalu bertanya kepadanya”.
Farrukh: “Anda belum menyebutkan nasabnya?”
Fulan: “Dia adalah Ar-Rabi’ah putra Farrukh yang memiliki kunyah (julukan) Abu Abdurrahman. Tak lama dilahirkan setelah ayahnya meninggalkan Madinah sebagai mujahid fi sabilillah, lalu ibunya memelihara dan mendidiknya. Tetapi sebelum shalat tadi orang-orang ramai mengatakan ayahnya telah datang kemarin malam.”
Tiba-tiba meleleh air mata Farrukh, tanpa lawan bicaranya mengerti mengapa Farrukh melelehkan air matanya.
Sesampai di rumah isterinya Ummu Rabi’ah melihat suaminya meneteskan air matanya, dan bertanya kepada suaminya, Farrukh : “Ada apa wahai Abu Abdirrahman?” Suaminya menjawab : “Tidak ada apa-apa. Aku melihat putraku berada dalam kedudukan ilu dan kehormatan yang tinggi, yang tidak kulihat pada orang lain”, tukasnya.
Di ujung kehidupan itu, Ummu Rabi’ah bertanya kepada suaminya, “Menurutmu manakah yang lebih engkau sukai, uang 30.000 dinar, atau ilmu dan kehormatan yang telah dicapai putramu?”. Farrukh menjawab : “Demi Allah, bahkan ini lebih aku sukai dari pada dunia dan seisinya”, ucapnya.
Begitulah kisah generasi Tabi’in yang penuh kemuliaan, dan peranan seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya berjihad ke negeri yang sangat jauh, selama tiga puluh, dan dapat mendidik putranya menjadi seorang ulama besar dan memiliki ilmu dan kehormatan yaitu Ar-Rabi’ah. Wallahu’alam.